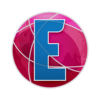Menuju swasembada beras yang berkesinambungan

Petani menjaga tanaman padi dari ancaman hama burung di lahan sawah tadah hujan, Desa Meunasah Mon Cut, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (24/8/2025). Pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan yang masuk dalam salah satu agenda prioritas APBN tahun 2026 dalam upaya mencapai swasembada pangan, terutama beras dan selain jagung. ANTARA FOTO/Ampelsa/tom. (ANTARA FOTO/AMPELSA)
Petani menjaga tanaman padi dari ancaman hama burung di lahan sawah tadah hujan, Desa Meunasah Mon Cut, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (24/8/2025). Pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan yang masuk dalam salah satu agenda prioritas APBN tahun 2026 dalam upaya mencapai swasembada pangan, terutama beras dan selain jagung. ANTARA FOTO/Ampelsa/tom. (ANTARA FOTO/AMPELSA)
Swasembada beras kembali menjadi topik yang mengemuka dalam percaturan kebijakan pangan nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan lantang menyuarakan optimismenya bahwa dalam tiga bulan ke depan Indonesia akan mampu kembali memproklamirkan diri sebagai bangsa yang mampu mewujudkan swasembada beras.
Pernyataan optimisme swasembada beras ini tentu memberi harapan, namun juga menimbulkan pertanyaan besar tentang swasembada yang akan diraih kali ini akan bersifat musiman, atau dapat benar-benar berkelanjutan.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini beberapa kali berhasil mencapai swasembada beras, tepatnya pada tahun 1984 dan 2022.
Pengakuan internasional dari lembaga pangan dunia, seperti FAO maupun IRRI, menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan swasembada beras tersebut diakui dunia.
Hanya saja, capaian swasembada beras itu belum bisa disebut permanen. Setiap kali terjadi anomali cuaca, musim kering berkepanjangan, atau dampak El Nino, kondisi swasembada seketika goyah dan impor beras dalam jumlah fantastis menjadi pilihan tak terhindarkan.
Inilah yang disebut swasembada beras musiman, yakni kondisi di mana produksi dalam negeri mencukupi pada satu musim, tetapi tidak mampu bertahan sepanjang tahun.
Swasembada beras musiman tentu bukan tanpa manfaat. Dalam periode tertentu, ketersediaan beras domestik meningkat dan ketergantungan impor bisa ditekan. Akan tetapi, sisi negatifnya adalah rentannya stabilitas harga dan pasokan pada musim lain.
Ketergantungan pada iklim dan pola panen membuat capaian swasembada beras tersebut rapuh. Padahal, masyarakat membutuhkan kepastian pasokan beras sepanjang waktu, bukan hanya ketika panen raya berlangsung.
Perdebatan mengenai swasembada beras musiman dan swasembada berkelanjutan menjadi semakin relevan ketika Presiden Prabowo menyatakan tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam kurun waktu maksimal empat tahun, bahkan disebut bisa tercapai hanya dalam dua tahun.
Pernyataan itu disampaikan dalam peresmian Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, setelah menerima masukan dari para menteri terkait pangan.
Pernyataan tersebut tentu mengundang rasa ingin tahu tentang masukan apa yang membuat Presiden begitu yakin dengan target ambisius swasembada beras ini, sementara pengalaman menunjukkan bahwa swasembada pangan jauh lebih kompleks daripada sekadar swasembada beras.
Perlu disadari bahwa swasembada pangan adalah akumulasi dari swasembada berbagai komoditas strategis, mulai dari swasembada beras, jagung, kedelai, daging, gula, bawang putih, hingga bahan pangan lain.
Menyatukan semuanya, termasuk swasembada beras, dalam rentang waktu dua tahun bukan pekerjaan sederhana. Pengalaman sebelumnya pun menunjukkan bahwa target ambisius swasembada Pajale (padi, jagung, kedelai) di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman belum seluruhnya tercapai, khususnya untuk kedelai.
Apalagi jika bicara di luar swasembada beras, seperti daging sapi atau bawang putih, yang hingga kini masih jauh dari harapan.
Pantang menyerah
Di balik segala tantangan, tekad besar bangsa untuk mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras, jangan pernah padam.
Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa semangat pantang menyerah sering kali mampu mengubah yang mustahil menjadi mungkin.
Diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan terobosan inovatif untuk menghadapi hambatan klasik, seperti keterbatasan lahan, ketersediaan air, distribusi pupuk, hingga tantangan perubahan iklim.
Arah yang harus dikejar jelas, bukan swasembada yang on trend atau hanya bertahan saat cuaca mendukung, melainkan swasembada beras yang berkelanjutan.
Artinya, sistem pangan nasional harus dirancang sedemikian rupa, sehingga mampu bertahan dalam berbagai kondisi, baik musim kemarau panjang, banjir, maupun gejolak pasar global.
Untuk itu, keberadaan grand design dan peta jalan yang jelas menjadi hal yang sangat penting. Tanpa arah kebijakan yang konkret, optimisme hanya akan tinggal sebagai retorika.
Pertanyaan mendesak yang perlu diajukan adalah apakah desain perencanaan menuju swasembada pangan berkelanjutan sudah ada, bagaimana peta jalannya, dan apakah benar dapat diwujudkan dalam dua tahun ke depan.
Publik tentu berhak mengetahui dokumen strategis semacam itu, bukan sekadar mendengar slogan atau janji. Keterbukaan ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawal, sekaligus memberi masukan.
Optimisme Presiden Prabowo yang menargetkan swasembada pangan dalam dua tahun memang patut diapresiasi.
Di satu sisi, target ini bisa menjadi pendorong semangat bagi semua pemangku kepentingan untuk bergerak lebih cepat, namun di sisi lain, tanpa pijakan yang kuat, ia berpotensi menjadi ekspektasi yang membebani.
Maka yang diperlukan sekarang adalah penjelasan lebih rinci tentang basis dari optimisme itu, kebijakan apa yang akan ditempuh, program apa yang akan diprioritaskan, dan dukungan apa yang dibutuhkan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.
Pelajaran berharga dari pencapaian swasembada beras di masa lalu adalah bahwa keberhasilan yang semu tidak bisa dijadikan pijakan.
Ketika hanya bergantung pada musim panen atau kondisi iklim yang mendukung, ketahanan pangan nasional akan selalu berada di ujung tanduk.
Sebaliknya, dengan pendekatan yang sistematis, berorientasi jangka panjang, dan berkelanjutan, Indonesia bisa membangun kemandirian pangan yang sejati.
Masyarakat tentu menginginkan kepastian, bukan sekadar kebanggaan sesaat. Swasembada beras yang berkelanjutan akan memberikan dampak besar mencakup stabilitas harga, kepastian pasokan, peningkatan kesejahteraan petani, dan kemandirian bangsa dalam menghadapi gejolak pangan global. Inilah yang harus menjadi arah utama dari setiap kebijakan pangan nasional.
Harapan publik sederhana, yakni jangan sampai swasembada beras dan pangan kembali menjadi sekadar perayaan musiman.
Capaian yang sifatnya sementara tidak akan membawa bangsa ini pada kemandirian sejati. Hal yang dibutuhkan adalah swasembada beras yang permanen, yang mampu bertahan melampaui perubahan musim, krisis iklim, dan gejolak pasar dunia.
Melalui semangat juang, kebijakan tepat, dan komitmen kuat, swasembada beras berkelanjutan bukanlah mimpi, melainkan cita-cita yang bisa diwujudkan demi masa depan bangsa.