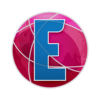Membangun kemandirian MRO nasional
Maintenance, Repair, and Overhaul, sektor strategis pada industri penerbangan, mencakup aktivitas pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan pada pesawat udara.

Ilustrasi - Aktivitas Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia, fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) di Bandara Hang Nadim Batam. (ANTARA FOTO/M N Kanwa/foc/aa.)
Ilustrasi - Aktivitas Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia, fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) di Bandara Hang Nadim Batam. (ANTARA FOTO/M N Kanwa/foc/aa.)
Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) adalah sektor strategis dalam industri penerbangan yang mencakup seluruh aktivitas pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan berkala terhadap pesawat udara, termasuk mesin, badan pesawat, avionik, serta sistem pendukung lainnya.
Fungsi MRO tidak sekadar menjamin keselamatan penerbangan, tetapi juga menjaga efisiensi operasional maskapai, memperpanjang usia pesawat, dan menjadi sumber nilai tambah ekonomi nasional.
Bagi negara kepulauan, seperti Indonesia, yang mengandalkan konektivitas udara untuk mobilitas ekonomi dan sosial, MRO sejatinya merupakan bagian dari sistem pertahanan dan kedaulatan udara.
Realitanya, saat ini menunjukkan tantangan serius. Lalu lintas penerbangan Indonesia, kini telah pulih signifikan, hampir setara dengan kondisi sebelum pandemi, tetapi hampir setengah dari perawatan pesawat nasional masih dilakukan di luar negeri, terutama untuk mesin dan komponen kritis.
Akibatnya, miliaran dolar potensi ekonomi, kesempatan kerja, dan penguasaan teknologi mengalir ke luar negeri. Padahal, potensi pasar MRO domestik diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 miliar dolar AS per tahun.
Situasi ini jelas tidak sejalan dengan semangat kemandirian industri dan amanat kedaulatan ekonomi yang kini menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mengoreksi ketergantungan ini, strategi nasional harus diarahkan pada pembentukan ekosistem MRO yang mandiri dan berdaulat, di mana setiap elemen industri, mulai dari produsen, operator, hingga lembaga pembiayaan, terkonsolidasi dalam sistem yang saling memperkuat.
Pemerintah perlu menugaskan Danantara sebagai lead integrator dan pemegang mandat kedaulatan keamanan penerbangan dalam konteks industri MRO nasional. Danantara memiliki posisi strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan pengelolaan BUMN aviasi, seperti PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF AeroAsia), PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), serta PT Dirgantara Indonesia (PTDI), agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Strategi konsolidasi yang dipimpin oleh Danantara juga harus memperhatikan arahan Presiden Prabowo mengenai perampingan jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Rasionalisasi ini bukan sekadar penyederhanaan administratif, tetapi langkah untuk memastikan seluruh perusahaan pelat merah menjadi lebih lincah, efisien, dan produktif, dengan fokus pada mandat strategis masing-masing sektor.
Untuk itu, integrasi dalam ekosistem MRO harus diarahkan agar setiap entitas BUMN memiliki spesialisasi dan saling melengkapi, bukan bersaing atau tumpang tindih.
Sebagai contoh, NTP dapat difokuskan pada keunggulan di bidang engine dan propulsi, GMF AeroAsia pada perawatan airframe dan komponen sistem penerbangan, sedangkan PTDI menjadi tulang punggung manufaktur dan rekayasa struktur. Dengan peran yang jelas, masing-masing dapat tumbuh, tanpa mengorbankan efisiensi nasional. Danantara berperan memastikan rantai pasok, pembiayaan, dan sertifikasi teknis berjalan terpadu, sehingga Indonesia dapat mencapai tingkat kemandirian yang berkelanjutan dalam sektor dirgantara.
Langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ini meliputi pembentukan pusat-pusat keunggulan MRO (Centers of Excellence) yang berfokus pada bidang tertentu, yaitu Airframe untuk perawatan struktur pesawat dan integrasi sistem utama; Engine Wide Body dan Narrow Body untuk penguasaan teknologi mesin dan komponen kritis; Component & Avionics sebagai basis bagi industri pendukung dan inovasi teknologi lokal.
Pusat-pusat keunggulan ini akan berfungsi sebagai core ecosystem yang mendorong tumbuhnya beberapa MRO tambahan di tingkat regional.
Dalam model ini, tiga, hingga empat MRO baru dapat muncul dengan potensi bisnis sekitar 125 juta dolar AS per tahun hanya dari kontribusi tenaga kerja dan subkontraktor lokal.
Selain menciptakan lapangan kerja, ekosistem ini akan menumbuhkan industri pendukung yang kuat, mulai dari precision engineering, non-destructive testing, hingga component refurbishment.
Untuk mendukung akselerasi, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin keberlanjutan kebijakan. Setidaknya ada tiga langkah strategis yang harus segera diwujudkan.
Pertama, regulasi keselamatan berbasis air operator certificate (AOC). Pemerintah dapat mewajibkan pesawat ber-AOC Indonesia untuk melakukan perawatan dasar di MRO bersertifikat nasional. Langkah ini sah secara internasional karena berbasis pada standar keselamatan, bukan proteksi industri.
Kedua, pembangunan fasilitas logistik khusus MRO. Melalui skema pusat logistik berikat (PLB), distribusi suku cadang pesawat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa terhambat biaya dan waktu kepabeanan.
Ketiga, pembentukan dana pengelolaan mesin pesawat (engine leasing fund). Skema ini memungkinkan investasi jangka panjang dan pengelolaan aset mesin di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada lembaga leasing asing, serta membuka peluang bagi pembiayaan kolaboratif antara PT SMI, PT PII, dan lembaga keuangan syariah.
Selain aspek teknis dan regulatif, keberhasilan ekosistem MRO juga bergantung pada pembentukan satuan tugas lintas kementerian permanen, dengan pusat keunggulan MRO nasional sebagai sekretariat teknisnya.
Satuan tugas ini sebaiknya dilegitimasi melalui peraturan presiden (perpres) agar memiliki kekuatan hukum dan menjamin konsistensi lintas periode pemerintahan. Dengan dasar hukum yang kuat, seluruh kebijakan dan kontrak terkait industri MRO tidak akan mudah berubah karena pergantian pejabat atau arah kebijakan sektoral.
Keberadaan satuan tugas juga menjadi mekanisme koordinasi antarpihak, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian, agar arah pembangunan industri dirgantara nasional terjaga sinkron dan selaras dengan kebijakan pertahanan nasional.
Dengan demikian, MRO bukan hanya bisnis komersial, melainkan penopang sistem keamanan dan kedaulatan penerbangan Indonesia.
Lebih jauh, strategi Danantara dalam membangun industri MRO harus berorientasi pada tiga pilar utama, yaitu kemandirian teknologi, melalui transfer pengetahuan dan penguasaan critical components; kemandirian ekonomi, dengan memperbesar porsi pekerjaan dalam negeri dan penghematan devisa; serta kemandirian SDM, melalui sertifikasi, pelatihan, dan kolaborasi pendidikan vokasi.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berpotensi menjadi hub MRO Asia Tenggara dalam lima hingga tujuh tahun ke depan.
Jika separuh lebih dari seribu pesawat yang terdaftar di Indonesia dapat dirawat di dalam negeri, penghematan devisa dan dampak ekonomi langsung dapat mencapai ratusan juta dolar per tahun, sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru bagi teknisi dan insinyur penerbangan Indonesia.
Membangun kemandirian MRO bukan semata isu efisiensi, tetapi soal kedaulatan ekonomi, teknologi, dan bangsa.
Kini saatnya langkah besar diwujudkan: pemerintah mengunci arah melalui regulasi dan insentif yang konsisten, industri berkolaborasi membangun pusat keunggulan, dan lembaga pembiayaan memastikan keberlanjutan investasi.
Danantara, bersama GMF, NTP, PTDI, dan mitra strategis lainnya, menjadi tulang punggung ekosistem MRO Indonesia yang solid, gesit, dan berdaya saing tinggi. Indonesia memiliki potensi besar, kini tinggal memastikan bahwa langkahnya tidak lagi terseok oleh fragmentasi institusional. Saatnya industri MRO Indonesia tumbuh mandiri, berdaulat, dan menjadi kekuatan regional yang tangguh.
*) Teuku Gandawan Xasir adalah konsultan dan pakar di Institut Strategi Indonesia, praktisi teknologi dan komunikasi korporasi, alumnus ITB yang fokus pada kemandirian energi, pertahanan nasional, dan tata kelola industri berdaulat