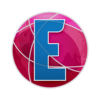Transformasi infrastruktur Indonesia, bersiap untuk lompatan paradigma

Ilustrasi - Proyek infrastruktur bidang Teknologi Informasi. (ANTARA/HO-IIF)
Ilustrasi - Proyek infrastruktur bidang Teknologi Informasi. (ANTARA/HO-IIF)
Infrastruktur merupakan fondasi dari kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Jika dahulu istilah ini hanya identik dengan jalan raya, jembatan, dan pelabuhan, kini definisinya berkembang jauh lebih luas.
Infrastruktur modern mencakup jaringan digital, energi terbarukan, pusat data, hingga koridor pengisian kendaraan listrik. Perubahan ini tidak bisa diabaikan oleh Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, 270 juta penduduk, dan ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia.
Pertanyaannya, apakah Indonesia siap melakukan lompatan paradigma dalam pembangunan infrastrukturnya, atau justru terjebak dalam pendekatan lama yang hanya berfokus pada beton dan baja?. Menurut McKinsey, kebutuhan investasi infrastruktur global hingga 2040 mencapai 106 triliun dolar AS. Asia diperkirakan menyerap lebih dari separuhnya, terutama akibat urbanisasi cepat dan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp6.445 triliun pada periode 2020–2024, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah hanya sekitar 37 persen dari total kebutuhan tersebut.
Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan sekitar Rp4.000 triliun yang harus diisi melalui partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP). Tanpa strategi inovatif, Indonesia akan kesulitan mengejar ketertinggalan.
Pembangunan infrastruktur Indonesia dalam satu dekade terakhir memang menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan tol sepanjang lebih dari 2 ribu kilometer berhasil dibangun sejak 2015, disertai pembangunan bandara, pelabuhan, dan bendungan.
Fokus besar pada proyek fisik ini seharusnya dilengkapi dengan investasi pada infrastruktur modern: jaringan digital, energi bersih, dan fasilitas logistik cerdas. Faktanya, hingga kini akses internet cepat baru menjangkau sekitar 70 persen desa, dan kualitas jaringan masih timpang antarwilayah. Padahal, digitalisasi adalah tulang punggung ekonomi masa depan, terutama di era perdagangan elektronik dan kecerdasan buatan.
Selain itu, sektor energi juga menuntut perubahan besar. Indonesia masih bergantung pada batu bara yang menyumbang lebih dari 60 persen pembangkit listrik nasional. Padahal, komitmen transisi energi menuju net zero emission pada 2060 membutuhkan investasi besar dalam energi terbarukan.
International Energy Agency (IEA) memperkirakan Indonesia membutuhkan lebih dari 20 miliar dolar AS per tahun untuk mempercepat transisi energi. Salah satu langkah strategis adalah memperluas pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta mengembangkan jaringan listrik pintar (smart grid) yang mampu mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan konsumsi masyarakat.
Pusat data juga menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur masa depan. Lonjakan penggunaan kecerdasan buatan dan layanan digital mendorong kebutuhan kapasitas pusat data yang diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat secara global pada 2030.
Indonesia sendiri mulai dilirik sebagai hub pusat data di Asia Tenggara, dengan investasi raksasa teknologi, seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Namun, pusat data membutuhkan pasokan energi besar dan stabil, sehingga pengembangan sektor ini harus diiringi dengan kebijakan energi hijau agar tidak justru menambah beban karbon.
Keterhubungan antar-sektor juga semakin nyata. Misalnya, pembangunan koridor kendaraan listrik (EV) memerlukan integrasi antara otoritas jalan tol, PLN sebagai penyedia listrik, serta perusahaan teknologi finansial untuk sistem pembayaran.
Hingga pertengahan 2025, jumlah kendaraan listrik di Indonesia baru mencapai sekitar 100.000 unit, masih jauh dari target 13 juta unit pada 2030. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan stasiun pengisian daya, yang baru mencapai sekitar 2.000 unit di seluruh negeri. Jika tidak ada percepatan investasi, target elektrifikasi transportasi akan sulit tercapai.
Maka, yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya pembangunan infrastruktur sektoral, melainkan pola pikir lintas sektor (cross-vertical thinking). Infrastruktur energi harus terhubung dengan transportasi, digital dengan sosial, serta pertanian dengan pengelolaan limbah.
Sebagai contoh, limbah pertanian dapat diolah menjadi biogas untuk mendukung pembangkit listrik lokal. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menambah aset fisik, tetapi juga menciptakan ekosistem berkelanjutan. Di sinilah peran modal swasta menjadi krusial. Data menunjukkan bahwa aset infrastruktur swasta global yang dikelola melonjak dari 500 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 1,5 triliun dolar AS pada 2024.
Indonesia bisa meniru strategi negara lain untuk menarik investasi swasta. Brasil, misalnya, berhasil mendatangkan investasi 128 miliar dolar AS ke sektor air dan sanitasi lewat kerangka hukum baru. Hong Kong menggunakan kenaikan nilai tanah untuk membiayai sistem MRT. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa melalui reformasi regulasi, transparansi proyek, dan skema PPP yang lebih menarik bagi investor.
Selain pembiayaan, tantangan serius lainnya adalah tenaga kerja. Sektor konstruksi di Indonesia masih menghadapi kekurangan pekerja terampil, khususnya di bidang teknologi konstruksi digital, energi terbarukan, dan otomasi.
Menurut Kadin, Indonesia membutuhkan lebih dari 9 juta talenta digital pada 2030, sementara setiap tahun hanya sekitar 600 ribu lulusan teknologi yang dihasilkan. Tanpa percepatan pengembangan SDM, proyek infrastruktur modern berisiko terganjal. Pemerintah perlu berinvestasi besar pada pendidikan vokasi, pelatihan energi terbarukan, serta transfer teknologi dari proyek-proyek strategis.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Pertama, memperluas definisi infrastruktur dalam perencanaan pembangunan nasional. Tidak cukup hanya membangun jalan tol dan pelabuhan, tetapi juga memastikan ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, dan energi terbarukan.
Kedua, menutup kesenjangan pembiayaan melalui PPP yang jelas dan adil bagi investor. Proyek harus dirancang dengan skema risiko yang transparan, termasuk jaminan keberlanjutan regulasi.
Ketiga, mempercepat digitalisasi perencanaan infrastruktur melalui adopsi digital twin yang memungkinkan pemerintah memodelkan skenario biaya, dampak lingkungan, dan proyeksi pertumbuhan. Digital twin dapat meningkatkan efisiensi hingga 30 persen, sebuah nilai besar bagi APBN yang terbatas.
Keempat, memperkuat tata kelola proyek agar bebas dari korupsi dan inefisiensi. World Bank mencatat, biaya pembangunan infrastruktur di Indonesia masih 20–30 persen lebih mahal dibanding rata-rata global akibat birokrasi dan pemborosan. Tanpa pembenahan tata kelola, setiap rupiah investasi tidak akan menghasilkan dampak optimal.
Kelima, mempercepat transisi energi dengan target yang lebih ambisius. Misalnya, memperluas pembangkit surya atap di kawasan industri, mempercepat pembangunan pembangkit panas bumi, dan memberikan insentif fiskal bagi investasi energi terbarukan.
Singkatnya, infrastruktur Indonesia kini berada pada titik balik yang menentukan. Jika tetap terjebak dalam paradigma lama, Indonesia hanya akan membangun jalan tanpa menyiapkan jalur digital dan energi masa depan.
Namun, jika berani melakukan lompatan paradigma, memanfaatkan modal swasta, memperkuat SDM, dan mengintegrasikan teknologi, Indonesia dapat menjadikan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus penopang keberlanjutan.