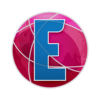Peran media massa arus utama di era fabrikasi kebenaran

LBocah viral, Muhammad Badru, saat menari di sela-sela unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah/am.
LBocah viral, Muhammad Badru, saat menari di sela-sela unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Gejolak sosial yang melanda Indonesia pada periode Agustus hingga awal September 2025 menandai sebuah babak baru dalam artikulasi aspirasi publik. Di tengah riuh rendahnya aksi massa dan ketegangan politik, muncul satu fenomena yang mendefinisikan ulang lanskap aktivisme warga: “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Gerakan ini bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan situasi nyata bagaimana sebuah narasi terstruktur mampu membelah kabut disinformasi, lantas memaksa institusi negara untuk mendengar. Namun, efektivitas dan keberhasilannya tentu tidak berdiri tunggal.
Di era fabrikasi kebenaran, di mana hoaks dan opini publik dapat dikonstruksi untuk membiaskan fakta esensial, muncul pertanyaan krusial, bagaimana gerakan ini mampu mencapai koherensi dan legitimasi nasional di waktu yang pendek?
Jurnalis, sekaligus pemikir Walter Lippmann, lewat buku Public Opinion (1922), mengelaborasi konsep fabrikasi persetujuan (manufacture of consent). Menurutnya, elite politik sengaja menyederhanakan dan memfabrikasi kebenaran untuk membentuk persepsi umum, demi mengarahkan opini dan mendapatkan persetujuan publik.
Gagasan tersebut kemudian diperdalam Noam Chomsky dan Edward Herman dalam karyanya Manufacturing Consent (1988), di mana model propaganda tersentralisasi di pemilik modal dan elit politik. Selanjutnya “kebenaran” yang sampai ke publik merupakan produk hasil seleksi dan konstruksi yang sistematis.
Ketika percakapan demokratis di media sosial ada pihak tersudut, biasanya akan muncul upaya meredamnya, baik dengan mengalihkan isu lewat trending topic maupun serangan siber berupa caci maki massal (troll bombing).
Meski kini cara publik mengonsumsi informasi telah berubah, media arus utama telah memainkan perannya sebagai validator dan amplifikator melalui kanal-kanal distribusinya, yakni mengubah kampanye digital menjadi agenda politik yang tak terhindarkan, dengan tetap proporsional dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Tuntutan terstruktur
Berbeda dari gerakan-gerakan reformasi sebelumnya yang lahir dari kantong-kantong aktivis atau dewan mahasiswa, “17+8 Tuntutan Rakyat” dibidani elemen warga di era digital yang memungkinkan saling terhubung secara singkat.
Gerakan ini lahir dari inisiatif berbagai warga di era digital, lalu dirancang secara khusus oleh para pemengaruh (influencer) dan figur publik agar menjadi viral. Dengan slogan kuat --Transparansi, Reformasi, Empati-- serta identitas visual jelas, kampanye ini berhasil menjadi wadah pemersatu aneka keresahan masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah.
Partisipasi aktif dari warga yang peduli terhadap hak publik melahirkan konsep yang disebut Mezey (2008) sebagai warga negara kompeten (competent citizens). Ciri utama warga negara ini adalah kesadaran mereka akan hak-hak pribadi dan sesama, yang disertai dengan kapasitas untuk menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak tersebut secara kolektif dan terstruktur.
Sejalan dengan hal ini, Tocqueville dalam karya klasiknya Democracy in America (1835) menyoroti bahwa partisipasi aktif warga dalam urusan publik serta adanya masyarakat sipil yang hidup, merupakan kunci utama bagi keberhasilan sebuah negara demokrasi.
Pada fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat, kecerdasan strategisnya terletak pada struktur tuntutan itu sendiri: 17 poin jangka pendek dengan tenggat waktu mendesak dan 8 poin jangka panjang untuk reformasi sistemik.
Struktur ini menyediakan dua hal penting, tekanan politis yang segera dan visi perubahan berkelanjutan. Ini adalah sebuah evolusi dari sekadar teriakan protes di jalanan menjadi sebuah proposal kebijakan yang terperinci dan menuntut akuntabilitas.
Namun, sehebat apa pun sebuah kampanye digital, jika tidak menjejak di dunia nyata, ia berisiko bak idiom klasik: “tempest in a teacup”. Di sinilah terjadi simbiosis strategis, pertukaran informasi jagat digital dan situasi nyata. Gerakan mahasiswa, dengan legitimasi historisnya, turun ke jalan, berpadu dengan mengadopsi “17+8 Tuntutan Rakyat” sebagai pernyataan perjuangan mereka. Mereka memberikan wajah dan energi fisik pada tuntutan yang lahir di ranah digital.
Di tengah lanskap informasi yang terpolarisasi, fabrikasi narasi kebenaran di tingkat elit, peran media arus utama menjadi penentu. Alih-alih hanya melaporkan peristiwa secara fragmentaris, bentrokan di satu sudut kota, aksi damai di sudut lain, media-media besar, seperti Kantor Berita ANTARA, Kompas, Tempo, Detik, dan Media Indonesia serta sejumlah media lainnya, secara serempak mengadopsi kerangka “17+8” sebagai narasi utama.
Ini adalah sebuah pilihan redaksional yang krusial. Dengan secara konsisten menggunakan frasa “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam judul dan isi berita, media arus utama melakukan lebih dari sekadar melaporkan; mereka melakukan validasi. Mereka mengangkat sebuah gerakan yang lahir dari media sosial menjadi platform tuntutan politik yang diakui secara nasional, bahkan dilakukan oleh diaspora Indonesia di luar negeri.
Dalam prosesnya, media tidak terjebak dalam narasi “kekacauan versus ketertiban” yang sering kali dimanipulasi untuk mendelegitimasi tujuan aksi protes atau demonstrasi. Sebaliknya, mereka memfokuskan wacana publik pada substansi tuntutan: reformasi DPR dan penyelenggara negara, akuntabilitas aparat, serta keadilan ekonomi.
Hasil studi Monash Data and Democracy Research Hub, dari Monash University yang dirilis 4 September lalu menyatakan polarisasi kelas dan anti-elit politik tidak muncul begitu saja di unjuk rasa publik kali ini, namun merupakan refleksi ketegangan kelas sosial yang sudah ada sejak lama.
Selama periode protes 25–31 Agustus 2025, percakapan daring di media sosial dan berita dipenuhi oleh dinamika emosi yang kuat. Menurut studi Monash University yang meneliti 13.780 unggahan unik, ditemukan bahwa meskipun mayoritas (70,9 persen) bersifat non-toksik, ada proporsi signifikan (29,1 persen) yang terindikasi toksik. Peningkatan tajam dalam toksisitas ini tercatat pada 28–30 Agustus, sebuah pola yang mencerminkan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta dan di sejumlah daerah.
Di era fabrikasi kebenaran, di mana narasi tandingan yang memecah belah dapat dengan mudah diciptakan, tindakan media arus utama ini berfungsi sebagai benteng. Media menyajikan kepada publik sebuah kebenaran yang koheren dan terverifikasi, sebuah daftar tuntutan konkret yang bisa dilacak dan ditagih, sebagai jangkar di tengah badai informasi.
Jurnalisme empati
Narasi ini diperkuat oleh sebuah pemicu emosional yang kuat: insiden tragis yang menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, oleh kendaraan taktis aparat. Media tidak hanya melaporkan fakta kematiannya, tetapi juga membingkainya sebagai simbol dari impunitas dan kekerasan negara.
Reportase jurnalistik yang empatik ini menyentuh nurani publik dan memberikan urgensi moral pada tuntutan, khususnya poin yang mendesak pembentukan tim investigasi independen. Pun demikian saat melaporkan peristiwa hilangnya nyawa di berbagai daerah, media arus utama tidak serta merta mengubahnya menjadi angka-angka, namun tetap menyebut nama korban sebagai penghormatan.
Kombinasi antara tekanan publik yang berbasis empati dan tuntutan terstruktur, yang diamplifikasi secara masif oleh media arus utama, terbukti efektif mendesak lahirnya solusi. Respons institusional, meskipun sebagian besar bersifat simbolis, bahkan normatif, menunjukkan dampak dari tekanan ini.
Langkah DPR yang cepat dalam membekukan kenaikan tunjangan adalah buah paling nyata dari gerakan ini. Ini adalah sebuah kemajuan konkret yang secara langsung menjawab salah satu tuntutan paling populer, sebuah solusi yang lahir dari artikulasi kemarahan publik yang terarah.
Pemerintah, melalui presiden dan para menterinya, juga merespons dengan retorika positif serta komitmen untuk mendengar. Meski langkah konkret atas tuntutan reformasi struktural yang mendalam dan komprehensif masih ditunggu, pintu dialog telah terbuka.
Kini, tantangan sesungguhnya di depan mata. Kemajuan jangka pendek tidak boleh melenakan. Delapan tuntutan jangka panjang, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, dan peninjauan ulang kebijakan ekonomi yang fundamental, adalah ujian sesungguhnya bagi komitmen negara. Di sinilah peran media massa arus utama kembali menjadi sentral.
Dalam perpektif Indonesia, Elemen Jurnalisme (Kovach dan Rosenstiel, 2001), terutama keutamaan kebenaran, keberpihakan pada warga, serta menjadi forum publik, dapat dipraktikkan institusi media arus utama, yakni menjadi rumah penjernih bagi informasi dan referensi utama bagi masyarakat.
Sajian media tidak berhenti pada paparan fakta, namun lebih dalam mengurai, menerjemahkan, mengungkap selubung peristiwa, serta memberdayakan warga agar semakin kritis dalam mengambil keputusan, baik yang nyata terjadi di lapangan, maupun dari percakapan di jagat digital, terutama pada akar permasalahan yang berfokus pada ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi.
Setelah berhasil menjadi kurator kebenaran dan fasilitator dialog, tugas media arus utama, selanjutnya, yaitu menjadi pengawas akuntabilitas yang gigih. Mereka harus terus menjaga agar delapan tuntutan jangka panjang itu tetap hidup dalam wacana publik, menagih janji para pembuat kebijakan, dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan bukan sekadar kosmetik atau kemasan normatif, melainkan transformatif.
Peristiwa Agustus-September 2025 telah memberikan sebuah cetak biru baru kepada publik, tentang kekuatan masyarakat sipil di era digital. Pelajaran berharganya adalah penegasan kembali peran jurnalisme yang bertanggung jawab. Bahwa di tengah kebisingan dan fabrikasi informasi, tugas utama media bukan hanya menyajikan fakta, tetapi juga loyal memberdayakan warga untuk menyingkap kebenaran yang esensial dan mendesak ditindaklanjuti bersama.