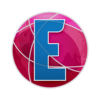Menelusuri esensi masalah Taiwan dalam perspektif Indonesia

Harryanto Aryodiguno, Ph.D President University, Indonesia.
Harryanto Aryodiguno, Ph.D President University, Indonesia.
Pernyataan Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, pada 7 November 2025 yang menyebut situasi Taiwan sebagai sebuah “krisis eksistensial” bagi Jepang segera memicu respons keras dari Beijing.
Hubungan Tiongkok–Jepang kembali menegang pada level yang jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
Sekali lagi, masalahTaiwan menjadi titik panas geopolitik Asia Timur, sekaligus menyingkap berbagai kesalahpahaman mendalam terkait sejarah Taiwan, prinsip hukum internasional, dan norma keamanan kawasan.
Di tengah hiruk-pikuk opini publik, banyak komentar yang terlalu politis, emosional, bahkan sepihak. Hal-hal ini menutupi inti persoalan. Untuk memahami sensitivitas, kompleksitas, dan dasar legitimasi masalahTaiwan, perlu dilihat melalui tiga kerangka utama:
1. Fondasi sejarah dan hukum dari tatanan internasional pasca-Perang Dunia II
2. Kewajiban hukum internasional yang melarang separatisme dan intervensi eksternal
3. Posisi sentral prinsip “keutuhan wilayah” dan “non-intervensi” dalam tradisi keamanan Asia
Hanya dengan melihat dari ketiga struktur tersebut, analisis dapat menyentuh inti masalah, bukan sekadar terjebak pada narasi geopolitik permukaan.
1. Pascaperang dan Dasar Hukum Internasional
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada 1945, kekuatan Sekutu—khususnya Amerika Serikat—membangun tatanan internasional baru dengan tujuan mengakhiri imperialisme dan kolonialisme, memulihkan wilayah yang pernah dianeksasi, serta menciptakan sistem internasional yang damai dan kooperatif.
Dalam kerangka inilah status Taiwan telah ditetapkan dengan jelas. Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam secara tegas menyatakan bahwa:
Taiwan harus dikembalikan kepada Tiongkok.
Ini bukanlah pernyataan yang ambigu atau “status belum ditentukan”. Pengaturan ini adalah bagian dari proses dekolonisasi Jepang yang sah secara hukum. Sejak 1945, masyarakat internasional pada umumnya mengakui bahwa:
Taiwan telah kembali di bawah kedaulatan Tiongkok dan statusnya sudah permanen.
Catatan sejarah Taiwan tahun 1945 juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyambut kedatangan “pemerintahan leluhur” dengan sukacita setelah 50 tahun kolonialisme Jepang.
Dengan demikian, masalahTaiwan tidak berawal dari sengketa kedaulatan, tetapi merupakan warisan dari perang saudara Tiongkok.
2. Dua Pemerintahan, Bukan Dua Negara: Taiwan sebagai “Perang Saudara yang Membeku”
Pembelahan politik antara Taipei dan Beijing tidak muncul dari pilihan politik kolektif masyarakat Taiwan, melainkan dari korupsi dan kegagalan administrasi pemerintah nasionalis pascaperang. Konflik 1945–1949 membuat Tiongkok terbelah, dan Perang Dingin membekukan kondisi itu hingga kini.
Dari perspektif ilmu politik:
Situasi dua pemerintahan adalah “perang saudara yang membeku”, bukan pemisahan internasional.
Karena itu, hukum internasional tetap memandang Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Keterlibatan negara luar dalam masalahTaiwan merupakan intervensi terhadap persoalan domestik Tiongkok, bukan dukungan terhadap dua negara berdaulat.
Mengabaikan konteks sejarah ini hanya akan menghasilkan analisis geopolitik yang keliru.
3.Hukum Internasional terhadap Separatisme
Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 melarang perusakan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Sistem hukum internasional secara konsisten menolak pendukung separatisme, kecuali jika terjadi pelanggaran HAM ekstrem seperti genosida.
Dengan demikian, dukungan terhadap “kemerdekaan Taiwan”:
• Tidak memiliki dasar hukum internasional, dan
• Berpotensi menciptakan “efek domino” separatisme di seluruh dunia.
Bagi Indonesia yang memiliki persoalan Papua, preseden semacam ini jelas berbahaya dan inkonsisten dengan kepentingan nasional.
4. Kesalahpahaman tentang “Taiwan” dan Ragam Identitas di Wilayah yang Dikuasai Taipei
Sering kali internasional hanya menyamakan “Taiwan” dengan “Pulau Taiwan”. Padahal wilayah yang berada di bawah administrasi Taipei mencakup Kinmen, Matsu, dan Penghu, di mana identitas, sejarah, dan politik masyarakatnya berbeda dari Taiwan daratan.
Mayoritas penduduk wilayah kepulauan itu secara historis melihat diri sebagai bagian dari Tiongkok, bukan negara Taiwan yang terpisah.
Karena itu muncul pertanyaan penting:
• Apakah wilayah seperti Kinmen dan Matsu bersedia dipaksa “keluar” dari Tiongkok?
• Siapa yang berhak menentukan masa depan mereka?
Persoalan ini menegaskan bahwa masalahTaiwan bukan hanya tentang Beijing dan Taipei, tetapi juga perbedaan internal masyarakat di wilayah administrasi Taiwan. Hakikatnya tetap merupakan urusan domestik Tiongkok.
5. Perspektif Asia: Relasionalitas Qin Yaqing dan Norma Keamanan Regional
Teoretikus hubungan internasional Qin Yaqing menekankan bahwa negara dalam konteks Asia bukan sekadar entitas kedaulatan, tetapi entitas relasional yang terbentuk dari jaringan sejarah, budaya, dan etika hubungan.
Dalam kerangka ini:
Upaya menjaga keutuhan wilayah adalah kewajiban etis, bukan sekadar klaim politik.
Karena itu posisi Tiongkok mengenai Taiwan tidak dapat disederhanakan sebagai “ekspansi nasionalis”, tetapi harus dilihat dalam konteks etika relasional Asia.
6. Norma ASEAN dan Sensitivitas terhadap Intervensi Eksternal
Amitav Acharya menjelaskan bahwa norma keamanan Asia—termasuk ASEAN—dibentuk oleh pengalaman historis terhadap imperialisme. Tiga prinsip utamanya adalah:
• Non-intervensi
• Kesetaraan kedaulatan
• Keutuhan wilayah
Dalam kerangka ini, pernyataan PM Jepang mudah dipandang sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal Tiongkok, serta memunculkan bayang-bayang historis “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
Sebagian besar negara Asia masih mengingat pengalaman kelam tersebut.
7. Sikap Indonesia dan ASEAN
Sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia memprioritaskan:
• Stabilitas kawasan
• Keamanan jalur perdagangan
• Pencegahan konflik kekuatan besar
• Penolakan terhadap setiap bentuk separatisme
Sikap Indonesia terhadap masalahTaiwan jelas:
Taiwan adalah persoalan internal antara masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan, bukan masalahyang harus ditentukan kekuatan eksternal.
Pendekatan ini konsisten dengan hukum internasional dan sejalan dengan kepentingan Indonesia.
Taiwan Bukan Sekadar masalahGeopolitik
masalahTaiwan menyentuh empat pilar utama:
1. Sejarah dan hukum internasional pascaperang
2. Larangan internasional terhadap separatisme
3. Norma keamanan Asia dan sensitivitas historis regional
4. Kepentingan kawasan Asia Tenggara akan stabilitas dan non-intervensi
Bagi Indonesia, prioritasnya jelas: menjaga ketertiban kawasan, menghormati kedaulatan negara, dan mendorong penyelesaian damai antara kedua belah pihak di dalam satu bangsa Tiongkok.
Hanya dengan menolak intervensi eksternal dan memahami akar historis serta struktur keamanan Asia, kawasan ini dapat membangun perdamaian yang sejati dan berkelanjutan.