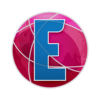30 April 2006: Wafatnya Pram, nyanyian bisu novelis yang melawan lewat tulisan
Minggu, 30 April 2006 dunia sastra Indonesia berduka. Setelah Sastrawan Pramoedya Ananta Toer meninggal dunia di rumahnya di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur.
 Sumber foto: https://bit.ly/3kbvjaw/elshinta.com.
Sumber foto: https://bit.ly/3kbvjaw/elshinta.com.Elshinta.com - Minggu, 30 April 2006 dunia sastra Indonesia berduka. Setelah Sastrawan Pramoedya Ananta Toer meninggal dunia di rumahnya di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur.
Sastrawan yang dua kali dinominasikan menerima Nobel ini meninggal karena komplikasi diabetes dan jantung. Pram, panggilan akrabnya melewati proses kehidupan yang tidak mudah selama 81 tahun.
Ia dipenjara, diasingkan bahkan pernah muncul keinginan Pram untuk mengakhiri hidupnya, menjadi rentetan panjang kisah hidupnya. Hanya buku dan menulis yang menjadi pelipur lara baginya saat menjalani hari-hari yang berat.
Pada 27 April 2006, kesehatan Pram makin melemah dan sempat tidak sadarkan diri. Selama 3 hari dirawat di Rumah Sakit Saint Carolus, ia bersikeras ingin pulang.
Kesehatan Pram menunjukkan kondisi lebih baik saat ada di rumah, bahkan ia sempat meminta rokok dan havermut (sejenis oat). Pihak keluarga kemudian memenuhi keinginannya namun hanya menempelkan rokok tanpa membakarnya.
Pada 30 April 2006 pukul 03.00 WIB kabar meninggal Pram tersebar hingga ke tetangga. Pada pukul 08.55 pagi di hari itu, Pramoedya Ananta Toer benar-benar wafat di usianya ke 81 tahun. Jenazah Pram kemudian dimakamkan di TPU Karet Bivak.
Saat keranda diangkat menuju ambulans sekitar pukul 13.00, tidak disangka lagu Internasionale dan Darah Juang berkumandang di tengah ratusan pelayat yang berdempetan di gang sempit Jalan Multikarya II/26, Utan Kayu, Jakarta Timur.
Kedua lagu tersebut memang identik dengan suasana perlawan kepada ketidakadilan. Bagi semua yang mengenalnya, Pram memang hidup untuk melawan selama separuh usianya.
Dibungkam rezim melawan lewat tulisan
Pram kelahiran Blora, Jawa Tengah, 2 Februari 1925 sudah menekuni dunia sastra sejak di bangku sekolah dasar. Idealisme dan keberaniannya mengkritik kebijakan pemerintah melalui karyanya membuatnya menghabiskan hampir separuh hidupnya di balik tahanan dan penjara.
Di era Sukarno, misalnya, ia masuk bui karena bukunya Hoakiau di Indonesia yang mengkritik kebijakan bagi etnis Tionghoa. Pada 1965, Pram diasingkan di Pulau Buru karena kiprahnya sebagai redaktur harian terbitan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) bentukan Partai Komunis Indonesia. Pada era Orde Baru, Pram kembali dijebloskan ke penjara selama 15 tahun karena tuduhan subversif.
Hidup di balik jeruji tak membuat Pram kehilangan semangat. Ia terus menelurkan berbagai karya sastra. Di antaranya tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Hal ini atas perintah Soeharto yang ditekan dunia internasional sehingga Pram boleh menulis kembali.
Saat zaman represi pada era Orde Baru, karya-karya Pram diberangus. Aktivitas Pram di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berhaluan kiri setidaknya memengaruhi pandangan orang tentang karya-karyanya yang dianggap berbau komunis.
Pram dibebaskan dari kamp Buru pada 1979. Hampir seluruh karyanya yang terbit di Indonesia setelah dia meninggalkan kamp penyiksaan itu dilarang oleh Kejaksaan Agung.
Namun, Hasta Mitra berani menjadi penerbit progresif yang pertama kali menerbitkan karya-karya Pram pada zaman Soeharto. Meski, para pembaca kala itu perlu sembunyi-sembunyi untuk bisa menikmati perenungan Pram dalam karya-karyanya.
Zaman bergulir, pada era Reformasi karya Pram justru bukan hanya menjadi bacaan sastra, melainkan menjadi potret lengkap kehidupan sosial, politik, dan sejarah masyarakat Indonesia yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari banyak orang.
Namun kenapa karya Pram begitu ditakuti pada zaman dahulu, tapi dirayakan pada era kini? Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menyebut Pram begitu getol melawan feodalisme.