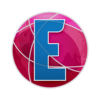Saat media arus utama harus bertarung di arena tak seimbang
Di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan setiap orang untuk menyuarakan pendapat di ruang digital, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah ruang digital hari ini benar-benar menciptakan ekosistem informasi yang adil, sehat, dan bisa dipertanggungjawabkan?
.jpeg) Haryo Ristamaji ketika menguji dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Radio. Foto: Dok Pribadi
Haryo Ristamaji ketika menguji dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Radio. Foto: Dok PribadiElshinta.com - Di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan setiap orang untuk menyuarakan pendapat di ruang digital, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah ruang digital hari ini benar-benar menciptakan ekosistem informasi yang adil, sehat, dan bisa dipertanggungjawabkan?
Sebagai wartawan radio yang telah lebih dari dua dekade menjalani hidup di ruang redaksi dan turun ke lapangan, saya merasakan sendiri betapa cepat dan kerasnya perubahan dalam dunia media. Dulu, berita disusun dengan hati-hati, diverifikasi berlapis, dan disiarkan dengan penuh tanggung jawab. Kini, berita sering dikalahkan oleh konten yang cepat, sensasional, dan viral yang lahir bukan dari ruang redaksi, tapi dari timeline media sosial.
Perubahan ini bukan sekadar soal teknologi atau selera audiens. Ini adalah tentang pertarungan yang tidak setara. Media arus utama atau mainstream dituntut mematuhi berbagai aturan dengan tunduk pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, pengawasan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Setiap kesalahan bisa berujung teguran, sanksi, bahkan gugatan hukum dan denda.
Sementara di sisi lain, siapa pun hari ini bisa menjadi “media” lewat akun pribadi. Tak perlu izin, tak ada redaktur, tak ada proses verifikasi, dan tak ada tanggung jawab etik. Informasi bisa tersebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan detik dan menit, tanpa ada jaminan bahwa informasi itu benar, adil, atau bahkan tidak berbahaya.
Bayangkan dua kapal berlayar dalam badai informasi. Satu kapal dilengkapi alat navigasi lengkap dan mengikuti aturan pelayaran yang ketat, itulah media arus utama. Sementara kapal lainnya bisa melaju sesuka hati, tanpa pemeriksaan muatan, tanpa awak profesional, dan tanpa rambu. Dalam situasi seperti ini, kita bukan sedang berlomba secara adil. Kita sedang menyaksikan satu pihak berusaha keras menjaga akurasi dan etika, sementara pihak lain bebas memutar kemudi tanpa arah yang jelas.
Ketimpangan ini berdampak besar, bukan hanya pada industri media itu sendiri, tapi pada apa yang dipercayai oleh publik. Ketika informasi dari media profesional kalah cepat dan kalah menarik dari unggahan di media sosial, maka perlahan tapi pasti, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada proses jurnalistik yang sebetulnya justru proses itulah yang menjaga khalayak dari manipulasi.
Hal terburuk dalam ketimpangan ini bukanlah bisnis media yang merosot meski itu sangat serius. Yang lebih mengkhawatirkan adalah runtuhnya fondasi informasi yang kredibel. Jika informasi yang kita konsumsi setiap hari didominasi oleh konten yang tak jelas sumbernya, maka yang hilang bukan hanya akurasi, tapi juga akal sehat bersama.
Kita butuh ruang digital yang adil. Ruang yang memberi tempat pada kebenaran, bukan hanya pada yang paling viral. Karena pada akhirnya, publik tidak hanya butuh tahu apa yang sedang terjadi, mereka butuh tahu mana yang benar dan yang tidak akurat. Skenario buruk yang dimungkinkan dapat saja terjadi:
1. Dominasi Informasi Tak Terverifikasi
Ketika algoritma dan popularitas menggantikan prinsip verifikasi dan etik jurnalistik, maka informasi yang viral bisa mengalahkan yang benar. Dalam jangka panjang, publik akan sulit membedakan antara kebenaran dan kebisingan. Informasi yang seharusnya menjadi panduan hidup bersama akan tertutup oleh banjir opini, sensasi, dan kabar yang belum tentu benar.
Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, tapi ancaman terhadap cara kita membentuk pikiran, mengambil keputusan, dan menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, semua pihak pemerintah, media, dan masyarakat harus mulai peduli dan bertindak secara nyata. Literasi, regulasi, dan etika harus menjadi fondasi bersama dalam membangun ruang informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Jika tidak, akal sehat publik sedang dipertaruhkan dalam gelombang yang tidak lagi bisa dikendalikan. Masyarakat akan lebih percaya pada konten yang cepat dan bombastis ketimbang berita yang sahih/benar dan berimbang.
2. Erosi Kepercayaan Publik terhadap Media Profesional
Media arus utama bisa dianggap "tidak relevan" atau "terlalu lambat" hanya karena mereka mengikuti prosedur etik. Padahal justru di sanalah letak tanggung jawab jurnalistik. Jika publik kehilangan kepercayaan pada media kredibel, maka penopang demokrasi akan runtuh, karena masyarakat kehilangan pegangan informasi yang valid untuk membuat keputusan sosial dan politik.
Jika publik kehilangan kepercayaan pada media yang kredibel, maka sesungguhnya kita sedang menggoyahkan salah satu tiang utama penyangga demokrasi. Demokrasi tidak bisa hidup tanpa informasi yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan, dan disampaikan secara berimbang. Masyarakat yang tidak lagi mempercayai media profesional akan kesulitan memilah mana fakta dan mana manipulasi, mana kritik konstruktif dan mana adu domba.
Tanpa panduan informasi yang valid, keputusan sosial dan politik masyarakat pun menjadi rapuh karena didasarkan bukan pada kebenaran, melainkan pada kebisingan, spekulasi, dan opini tanpa dasar. Hal ini bisa berujung pada polarisasi, ketidakstabilan sosial, dan menurunnya kualitas partisipasi publik dalam demokrasi. Media kredibel bukan sekadar penyampai berita, tapi penjaga nalar publik. Ketika media ini dipinggirkan oleh banjir konten tanpa etika di media sosial, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya bisnis media tetapi masa depan bangsa yang membutuhkan rakyat yang melek informasi dan mampu mengambil keputusan yang bijak.
Maka dari itu, menjaga eksistensi dan integritas media kredibel adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, pelaku platform digital, dan tentu saja komunitas pers itu sendiri. Karena hanya dengan informasi yang jernih, kita bisa membangun masa depan yang terang.
3. Radikalisasi Opini dan Polarisasi Sosial
Media sosial, tanpa moderasi yang memadai, kerap kali bukan menjadi ruang dialog yang sehat, melainkan justru memperkuat bias pribadi dan menciptakan apa yang disebut sebagai echo chambers yakni ruang gema digital saat seseorang hanya terpapar pada pandangan yang serupa dengan dirinya sendiri. Dalam ruang semacam ini, perbedaan pendapat tidak dihargai, kritik dianggap serangan, dan kebenaran menjadi relatif.
Ketika algoritma hanya menyajikan konten yang memperkuat keyakinan pengguna, maka terbentuklah realitas yang semu. Opini pribadi dengan mudah disamakan dengan fakta, dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin terbelah tidak karena fakta yang berbeda, tetapi karena versi realitas yang tak pernah mereka uji secara kritis dan fakta.
Lebih jauh, ruang gema ini mempercepat proses radikalisasi opini. Ketika individu hanya mendengar satu sisi argumen secara terus-menerus, tanpa tantangan intelektual atau sudut pandang alternatif, mereka cenderung menganggap bahwa pandangan berbeda adalah ancaman. Situasi ini adalah seperti tanah subur bagi intoleransi, fanatisme, bahkan kekerasan digital dan fisik.
Tanpa intervensi baik dalam bentuk regulasi, edukasi literasi digital, maupun kehadiran media yang kredibel media sosial berisiko menjadi arena yang membentuk generasi yang reaktif, rentan disusupi paham ekstrem, dan kehilangan daya nalar kritis. Karena itu, harus disadari, membiarkan ruang digital tumbuh tanpa kendali berarti melepaskan tanggung jawab atas kualitas demokrasi, kohesi sosial, dan masa depan generasi penerus. Literasi bukan pilihan, moderasi bukan sensor. Keduanya adalah fondasi penting untuk menciptakan ruang digital yang tidak hanya bebas, tetapi juga sehat dan beradab.
Ketika masyarakat terjebak dalam gelembung informasi yang sempit, kemampuan untuk berdialog dan berpikir kritis melemah. Ini bisa memperparah polarisasi, intoleransi, dan bahkan konflik horizontal.
4. Lumpuhnya Fungsi Media sebagai Watchdog
Media profesional, sejak awal kelahirannya, bukan hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memikul peran fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam demokrasi modern, mereka adalah watchdog pengawas independen yang memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Lewat kerja jurnalistik yang berbasis verifikasi, investigasi, dan keberanian untuk mengungkap fakta, media profesional melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kebijakan yang merugikan rakyat.
Namun, peran ini tidak bisa berjalan tanpa fondasi yang kokoh. Media memerlukan kepercayaan publik sebagai modal sosial, dan keberlanjutan finansial sebagai syarat eksistensi. Jika keduanya runtuh, maka kita akan menyaksikan kekosongan fungsi kontrol sosial yang selama ini diemban media. Ketika media tidak lagi dipercaya karena banjir disinformasi dan serangan naratif di ruang digital, atau ketika mereka tak mampu bertahan karena model bisnis yang digerus oleh platform digital tanpa tanggung jawab redaksional, maka siapa lagi yang akan menjadi penyeimbang kekuasaan?
Kita tidak bisa mengandalkan algoritma atau konten viral untuk memastikan transparansi pemerintahan, keadilan hukum, atau akuntabilitas kebijakan publik. Tanpa media yang kredibel dan independen, berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam senyap, tanpa sorotan dan tanpa pertanggungjawaban. Situasi ini menciptakan ruang kekuasaan yang gelap dan tertutup, berbahaya bagi demokrasi dan merugikan masyarakat luas.
Inilah mengapa membiarkan media profesional tumbang bukan sekadar kehilangan sumber berita, melainkan kehilangan salah satu pilar utama negara demokratis. Menjaga keberlanjutan dan integritas media bukan hanya tugas para pelaku industri, tapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Dukungan terhadap media kredibel adalah investasi sosial. Karena ketika kekuasaan tidak lagi memiliki penyeimbang yang efektif, maka yang akan kehilangan suara bukan hanya jurnalis tetapi kita semua. Ini bisa membuka peluang lebih besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran HAM.
5. Generasi Muda Kehilangan Orientasi Informasi
Anak-anak muda saat ini tumbuh di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform media sosial yang hampir tanpa batas. Tanpa dibekali dengan literasi digital yang memadai, mereka berisiko mengadopsi pola pikir yang serba instan menerima informasi tanpa cek fakta, cepat percaya pada konten yang sensasional, dan kurang mampu memilah mana yang benar-benar berkualitas dan relevan. Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap disinformasi yang merajalela, yang tak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi membentuk pandangan yang salah tentang dunia sekitar.
Lebih jauh lagi, minimnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan konteks sosial-politik membuat generasi muda ini miskin wawasan tentang identitas nasional, tanggung jawab sosial, dan makna demokrasi. Mereka cenderung terjebak dalam ruang-ruang gema (echo chambers) yang memperkuat opini sempit, yang seringkali dibentuk oleh algoritma media sosial demi engagement, bukan kebenaran atau kemajuan.
Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, kita menghadapi risiko besar: lahirnya generasi yang mudah dimanipulasi oleh propaganda, hoaks, atau kepentingan politik tertentu. Mereka bisa menjadi apatis, tidak peduli terhadap isu-isu publik, dan kurang memiliki keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, masa depan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya yang seharusnya menjadi agen perubahan dan pelopor kemajuan.
Oleh sebab itu, memperkuat literasi digital di kalangan anak muda bukan sekadar kebutuhan, melainkan kewajiban bersama. Pemerintah, pendidik, media, dan keluarga harus bersinergi untuk membekali dengan kemampuan kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen pasif media sosial, tetapi juga menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan berdaya dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa.
Ketimpangan Aturan: Media Arus Utama vs Media Sosial
Media arus utama di Indonesia bekerja di bawah standar etik yang ketat. Jurnalis harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), terverifikasi oleh Dewan Pers, dan diawasi oleh regulasi dari Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan satu kesalahan redaksional bisa berujung pada sanksi permintaan maaf publik, hak jawab, sanksi denda administratif terhadap pelanggaran isi siaran di lembaga penyiaran atau adanya kalusa pencabutan izin IPP atau ISR dalam kondisi tertentu.
Sebaliknya, media sosial hari ini menjadi "media massa de facto" tanpa kewajiban etik yang sama. Siapapun bisa menjadi penyebar informasi, membentuk opini publik, bahkan memprovokasi konflik sosial tanpa proses verifikasi, klarifikasi, dan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Akibatnya, playing field menjadi timpang dan tidak sehat.
Dampak Ketimpangan: Kacau Balau Narasi Publik
Ketimpangan ini bukan hanya soal bisnis media, tapi juga menyangkut integritas ruang publik. Hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian kini viral lebih cepat dibanding klarifikasi. Opini personal seolah lebih penting daripada liputan jurnalistik yang melalui proses verifikasi.
Lebih buruk lagi, media arus utama yang berpegang pada prinsip kehatihatian justru dianggap lamban, membosankan, bahkan kurang menarik. Padahal di sinilah letak pertanggungjawaban informasi yang selama ini menjadi tiang penyangga demokrasi.
Jika fenomena ini dibiarkan, kita akan menghadapi risiko erosi kepercayaan publik terhadap media yang kredibel, dan lebih jauh lagi, terhadap institusi-institusi demokrasi itu sendiri.
Jalan Tengah Menuju Ruang Digital yang Setara dan Sehat
Menghadapi ketimpangan dan tantangan yang kompleks di lanskap informasi digital saat ini, solusi yang parsial atau sepihak tidak akan cukup. Diperlukan pendekatan yang strategis, menyeluruh, dan melibatkan semua pihak terkait mulai dari pemerintah, regulator, pelaku media, hingga masyarakat pengguna media. Hanya dengan sinergi yang baik dan kebijakan yang inklusif, kita bisa menciptakan ruang digital yang tidak hanya setara secara regulasi, tetapi juga sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan strategis dan menyeluruh, serta sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan:
1. Regulasi Setara untuk Semua Pelaku Informasi
Pemerintah, bersama Dewan Pers, Komidigi, Komisi Penyiaran Indonesia dan pemilik platform digital, harus menyusun kerangka regulasi yang memperlakukan media sosial dan media arus utama secara setara dalam konteks distribusi informasi. Akun atau kanal yang menyebarkan berita secara reguler harus tunduk pada prinsip verifikasi, transparansi sumber, dan pertanggungjawaban hukum.
2. Penegakan Hukum Digital yang Tegas
Sudah waktunya kita berhenti hanya pada imbauan dan label hoaks. Perlu ada mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar konten destruktif, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Penegakan ini harus adil dan berbasis bukti, dengan melibatkan aparat penegak hukum, penyedia platform, dan lembaga pengawas independen.
3. Penguatan Peran Media Kredibel sebagai Mitra Negara
Untuk isu-isu strategis seperti keamanan, pemilu, kebijakan publik, dan darurat nasional, negara tidak bisa menyerahkan narasi hanya pada media sosial. Media kredibel harus dilibatkan sebagai mitra utama untuk menyampaikan informasi resmi dan akurat. Ini bisa dilakukan melalui kemitraan jangka panjang berbasis kepercayaan dan nilai informasi publik.
4. Literasi Media sebagai Pilar Ketahanan Informasi
Kunci jangka panjang untuk menjaga kesehatan ruang digital adalah literasi publik. Sekolah, perguruan tinggi, komunitas, hingga rumah tangga harus mengajarkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Pemerintah dan media harus bergandengan tangan mengembangkan program literasi digital yang tidak hanya informatif, tapi juga partisipatif.
5. Inovasi dari Media Arus Utama Sendiri
Media profesional tidak boleh sekadar mengeluh. Kita juga perlu terus berinovasi dalam format, pendekatan naratif, dan distribusi konten. Teknologi harus dilihat sebagai alat, bukan ancaman. Eksperimen dengan format audio digital, siniar, visual interaktif, hingga kecerdasan buatan dapat menjadi senjata baru media untuk tetap relevan dan dipercaya.
Jadi, ruang digital hari ini bukan hanya arena berekspresi, tetapi juga medan pertarungan persepsi. Jika negara membiarkan ketimpangan ini terus terjadi, maka yang akan kalah bukan hanya media profesional, tetapi juga kualitas demokrasi dan kohesi sosial kita.
Saatnya semua pihak pemerintah, pelaku media, masyarakat, dan platform digital duduk bersama untuk menata ulang tatanan ruang informasi kita. Kita tidak boleh membiarkan suara yang paling nyaring menenggelamkan yang paling benar.
Mari kita jaga ruang informasi dengan adil, setara, dan bertanggung jawab. Karena di tengah tsunami informasi ini, publik butuh mercusuar bukan yang paling terang, tapi yang paling bisa dipercaya.***
Penulis: Haryo Ristamaji, S.Kom, M.I.Kom
Wartawan radio, 25 Tahun di dunia jurnalistik penyiaran radio. Jurnalis senior Radio Elshinta ini peraih berbagai penghargaan di bidang jurnalistik dan penyiaran. Ia aktif mendorong kolaborasi media, swasta, pemerintah, dan publik dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat