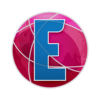Modernisasi jalan tengah mengangkat singkong nasional
Indonesia, negeri tropis yang subur, memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan singkong (cassava) sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku industri.
 Petani memperlihatkan ubi kayu (singkong) saat panen di Desa Rundeng, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (5/2/2025). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/tom.
Petani memperlihatkan ubi kayu (singkong) saat panen di Desa Rundeng, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (5/2/2025). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/tom.Elshinta.com - Indonesia, negeri tropis yang subur, memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan singkong (cassava) sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku industri.
Singkong memang bukan tanaman asli Indonesia, tetapi berasal dari Amerika Selatan yang dibawa ke Indonesia oleh Portugis melalui Filipina.
Di Bumi Nusantara singkong, yang dalam bahasa dunia disebut cassava, diterima secara luas oleh rakyat Nusantara sehingga dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.
Cassava begitu melekat di hati rakyat sehingga lahir beragam nama di setiap daerah. Sebut saja sampeu di Priangan, dangdeur di Banten, telo di Kutoarjo, dan ubi kayu di Jakarta.
Pemerintah Belanda juga mengembangkan singkong sebagai sumber pangan di negeri jajahan. Belanda pernah mempunyai perkebunan singkong ribuan hektar di Sukamandi. Saat ini lahan tersebut menjadi BBPadi dan Perum Benih SHS/Pertani.
Sedemikian membudidayanya singkong di tanah air, membuat tanaman introduksi asal Amerika Selatan itu kemudian dianggap sebagai komoditas lokal. Hal tersebut tercermin dari lagu "Anak Singkong" yang menggunakan produk singkong sebagai simbol komoditas lokal, sedangkan keju adalah simbol komoditas yang diimpor dari luar negeri.Dengan kata lain, singkong sudah dianggap melekat dengan Bangsa Indonesia.
Namun, ironisnya, ketika pemerintah menetapkan larangan impor tapioka, pati, dan produk turunan yang diekstrak dari umbi singkong, semua pihak justru terhenyak, menyadari bahwa ketergantungan Indonesia pada luar negeri sangat tinggi.
Tepung tapioka yang notabene berasal dari tanaman yang tumbuh di tanah sendiri, ternyata lebih dari 95 persen masih harus diimpor.
Bahkan, produk impor ternyata dapat hadir di tangan industri di Indonesia dengan harga lebih murah, kualitas lebih seragam, dan pasokan yang tersedia dalam jumlah besar. Sementara itu, produk dalam negeri belum mampu memenuhi tiga syarat utama tersebut.
Sebagai peneliti yang telah purnabakti, fakta tersebut membuat risih.
Sebuah diskusi terbuka dengan tema Dampak Larangan Impor Tapioka dan Prospek Hilirisasi Industri Singkong yang digelar Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) pada akhir bulan lalu telah menjadi pemantik ajang refleksi dan pencarian solusi atas kondisi ini.
Kunci dari semua ini adalah bagaimana Pemerintah Indonesia mampu membangun ekosistem produksi singkong nasional yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan, dengan menjadikan petani sebagai pelaku utama dalam sistem pertanian modern.
Salah satu akar persoalan ada pada disparitas antara keinginan pabrikan dan realitas di lapangan. Saat ini, harga pembelian singkong segar oleh pabrik hanya sekitar Rp1.350 per kilogram. Harga ini dianggap terlalu rendah oleh petani.
Sejauh ini, produktivitas singkong petani berkisar antara 15-17 ton per hektare. Padahal, potensi hasil singkong bisa mencapai 50-60 ton per hektar umbi segar dalam kondisi optimal. Bahkan hasil 35-45 ton per hektar pun sebenarnya bisa dicapai apabila petani menerapkan SOP budidaya secara konsisten.
Bimbingan penyuluhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat diperoleh dari Pelaku Industri Pengolahan atau dari Balai Penyuluhan di Kabupaten/Kecamatan.
Sayangnya, kualitas singkong petani, khususnya kadar pati yang hanya berkisar 17 persen, belum memenuhi harapan industri yang menghendaki kadar 20–24 persen.
Ini menjadi dilema klasik. Petani menilai harga terlalu rendah, pabrikan menganggap kadar pati kurang layak. Jalan tengahnya: Modernisasi.
Langkah Strategis
Penulis menawarkan lima langkah strategis untuk membangun sistem usaha tani singkong yang mampu menjawab tantangan larangan impor sekaligus menyejahterakan petani.
Pertama, diperlukan pengelolaan usaha tani cassava dengan pendekatan manajemen modern. Artinya, harus ada kontrak antara petani dan pabrik pengolah yang mencakup harga jual, persyaratan mutu, serta registrasi petani sebagai pemasok resmi.
Dengan model ini, petani akan mendapatkan kepastian pasar, sementara pabrikan mendapatkan kepastian pasokan.
Kedua, penyediaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang terbukti menghasilkan hasil optimal.
SOP ini harus diterapkan secara disiplin oleh petani, dengan bimbingan teknis dari penyuluh yang bisa berasal dari pihak pabrik atau lembaga riset.
Ketiga, kesepakatan harga jual singkong segar perlu dirancang agar memberikan insentif ekonomi yang layak bagi petani.
Perhitungan harga ini sebaiknya tidak hanya berdasarkan nilai pati, tetapi juga memperhitungkan potensi nilai tambah dari kulit singkong sebagai pakan dan ampasnya sebagai bahan baku produk sekunder.
Penelitian dari Universitas Brawijaya, misalnya, menunjukkan bahwa ampas singkong dapat diolah menjadi manitol, produk turunan yang bernilai tinggi.
Keempat, pabrik pengolah harus secara terbuka menyampaikan kebutuhan total singkong segar per tahun.
Transparansi ini penting untuk membangun perencanaan produksi di tingkat petani dan memastikan tidak terjadi oversupply atau kekurangan bahan baku.
Kelima, pemberian akses kredit usaha tani singkong bagi petani yang terdaftar perlu difasilitasi oleh perbankan, dengan pabrik pengolah bertindak sebagai penjamin atau avalis. Skema ini akan mendorong petani meningkatkan kapasitas produksinya tanpa terbebani risiko pasar.
Kelima langkah tersebut, jika dijalankan secara sistemik dan konsisten, akan membawa petani singkong ke dalam ekosistem pertanian modern.
Di sinilah peran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sangat penting, yakni menjadi katalisator yang menjembatani antara kebijakan, riset, petani, dan industri.
Modernisasi usaha tani singkong di Lampung atau daerah-daerah sentra lainnya bisa menjadi proyek percontohan nasional.
Tentu, implementasi dari seluruh rencana ini membutuhkan kesiapan kelembagaan, ketersediaan SOP yang operasional, dan komitmen semua pihak.
Penulis percaya, jika ada kemauan politik dan dukungan teknologi, Indonesia tak hanya bisa mandiri dalam urusan singkong, tapi juga menjadi pemain penting dalam pasar global tapioka dan produk turunannya.
*) Penulis adalah Tenaga Ahli di Aliansi Peneliti Pertanian Indonesia (APPERTANI) dan peneliti purnabakti Kementerian Pertanian.