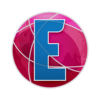Perang budaya dan senjata dalam konfilk Iran-Israel: Harga diri yang retak dilayar dunia
Di zaman ketika senjata bukan lagi satu-satunya yang memekakkan, sebuah pidato bisa lebih tajam dari peluru. Dan sebuah unggahan bisa lebih melukai daripada ledakan.
 Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra. Pengusaha dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid Jakarta, Vita Balqis D.
Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra. Pengusaha dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid Jakarta, Vita Balqis D.Elshinta.com - Di zaman ketika senjata bukan lagi satu-satunya yang memekakkan, sebuah pidato bisa lebih tajam dari peluru. Dan sebuah unggahan bisa lebih melukai daripada ledakan.
Kita menyaksikan Iran dan Israel bertarung bukan hanya di langit, tapi juga di layar digital. Bukan semata soal rudal dan drone, tapi tentang citra, harga diri, dan narasi yang dipertontonkan ke dunia. Konflik ini bukan hanya geopolitik, melainkan juga drama simbolik tentang siapa yang lebih beradab, siapa yang lebih terancam, siapa yang lebih patut didengar.
Yuval Noah Harari pernah menulis, “Perang hari ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang pesan.” Di era digital, pesan itu menjelma dalam potongan video, pidato penuh retorika, atau “cuitan” yang disebar dalam ribuan bahasa. Kata menjadi senjata, gambar menjadi propaganda, dan algoritma menjadi panglima.
Di tengah semua itu, kita nyaris tak sempat bertanya: wajah siapa yang sedang dipertaruhkan?
Ada sebuah teori dalam komunikasi antarbudaya yang jarang dibicarakan dalam liputan konflik bersenjata: Face Negotiation Theory dari Stella Ting-Toomey. Teori ini berbicara tentang “wajah”, bukan dalam arti harfiah, tapi martabat yang ingin dijaga. Harga diri kolektif yang ingin dihormati. Dalam konflik, setiap bangsa, bahkan setiap manusia, ingin dipahami, ingin dihormati. Keberadaannya ingin diakui, bukan dihapuskan oleh narasi lawan.
Iran, dengan budayanya yang simbolik dan penuh lapisan, membela kehormatan lewat kalimat-kalimat bernuansa religius dan sejarah perlawanan. Israel, sebaliknya, tampil gamblang, langsung, dan konfrontatif. Bagi satu pihak, kehormatan adalah kebersamaan umat. Bagi yang lain, kehormatan adalah hak untuk membela diri.
Bukan siapa yang lebih benar. Tapi siapa yang lebih didengar.
Ketika pidato Raisi dan Netanyahu menggema di Sidang Umum PBB, dunia tak hanya mendengar posisi politik. Dunia menyimak siapa yang tampil mulia, dan siapa yang tampak berbahaya. Setiap kata menjadi ritual mempertahankan “wajah”, Namun wajah siapa yang benar-benar terlihat di balik podium itu?
Di TikTok dan YouTube, pidato-pidato itu berubah menjadi potongan dramatis. Ada yang menyebut Raisi pahlawan Islam. Ada yang menyebut Netanyahu benteng dunia bebas. Tapi algoritma tak tahu konteks. Ia hanya tahu emosi. Ia hanya tahu apa yang membuat kita marah, menangis, membenci, dan membagi.
Lev Manovich menyebut ruang digital sebagai lanskap budaya baru. Tapi lanskap ini bukan padang yang luas. Ia lebih mirip ruang gema -echo chamber- di mana kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, dan lupa cara mendengar yang lain. Di titik ini, kita berhenti melihat dunia secara utuh.
Dalam medan pertempuran budaya Iran-Israel, saya bertanya: masih adakah ruang bagi mutual face? Bagi citra dan harga diri bersama yang tak perlu menang, hanya ingin saling dimengerti? Ada, kadang-kadang. Kita temukan dalam video jurnalis independen, dialog lintas agama, atau kampanye kemanusiaan yang nyaris tak viral.
Begitulah algoritma, ia tidak suka empati. Ia tak suka pelan-pelan. Ia suka kecepatan, kepastian, dan kemarahan yang meledak.
Ting-Toomey menulis, bahwa “wajah” atau martabat, bukan milik individu saja. Ia bisa kolektif, milik budaya, bangsa, atau agama. Ketika “wajah” itu dilukai, konflik menjadi lebih dari sekadar adu argumen. Ia menjadi luka yang dibela dengan seluruh harga diri.
Itulah sebabnya, konflik Israel-Iran di era digital bukan hanya tentang bom yang dijatuhkan atau drone yang dilepaskan. Ia tentang siapa yang lebih berhasil mempertahankan wajahnya atau menghancurkan wajah lawan di hadapan dunia.
Dan yang lebih menyedihkan, wajah itu kini dikendalikan oleh mesin. Oleh logika viral. Oleh kapitalisasi emosi.
Kita hidup di zaman ketika kehormatan bukan lagi disampaikan lewat surat diplomatik, tapi lewat unggahan tiga menit. Di zaman ketika budaya bisa disederhanakan menjadi hashtag, dan sejarah bisa diputarbalikkan lewat video editan.
Edward Said pernah mengingatkan, bahwa narasi bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Maka, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bijak dalam membangun narasi, siapa yang menjaga “wajah”, dan siapa yang menamparnya tanpa sadar, dengan simbol, kalimat, dan tayangan visual yang dibungkus algoritma.
Bagi saya, inilah tantangan utama komunikasi hari ini, menjaga “wajah” manusia dalam dunia yang serba cepat, bising, dan terpolarisasi. Bukan untuk memenangkan debat, tapi agar kita tetap bisa melihat kemanusiaan di balik layar. Agar wajah itu, wajah siapa pun, tidak hilang dalam kerumunan data dan kebisingan digital.
Karena setiap konflik, pada akhirnya bukan hanya tentang wilayah atau politik. Tapi tentang identitas yang takut dilupakan, dan kehormatan yang ingin dipertahankan.
Dan setiap “wajah” atau harga diri, seberapa pun retaknya, tetap ingin dimengerti.(Rizky Rian Saputra).